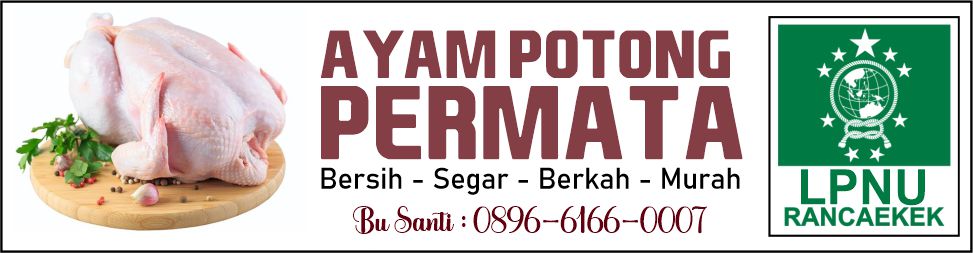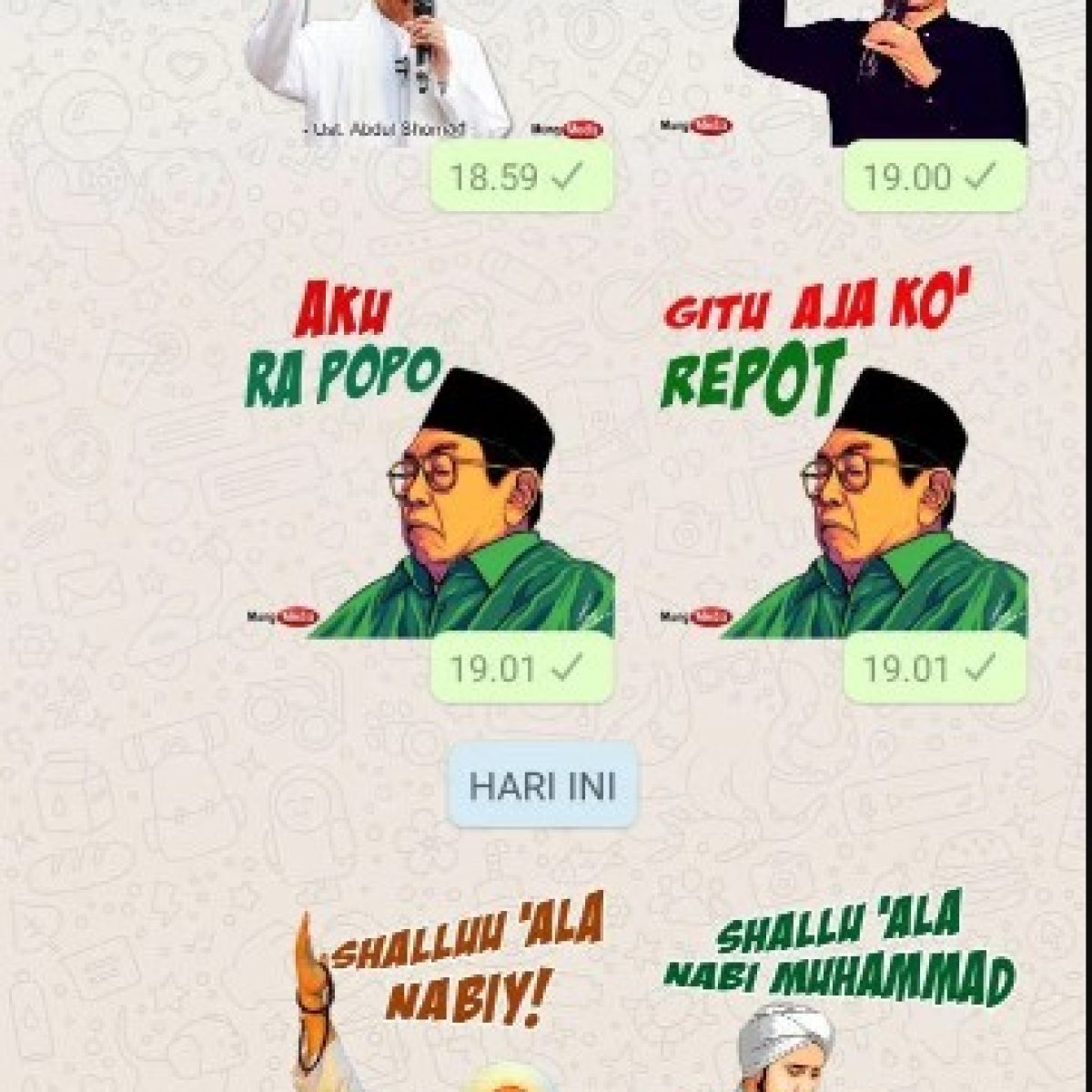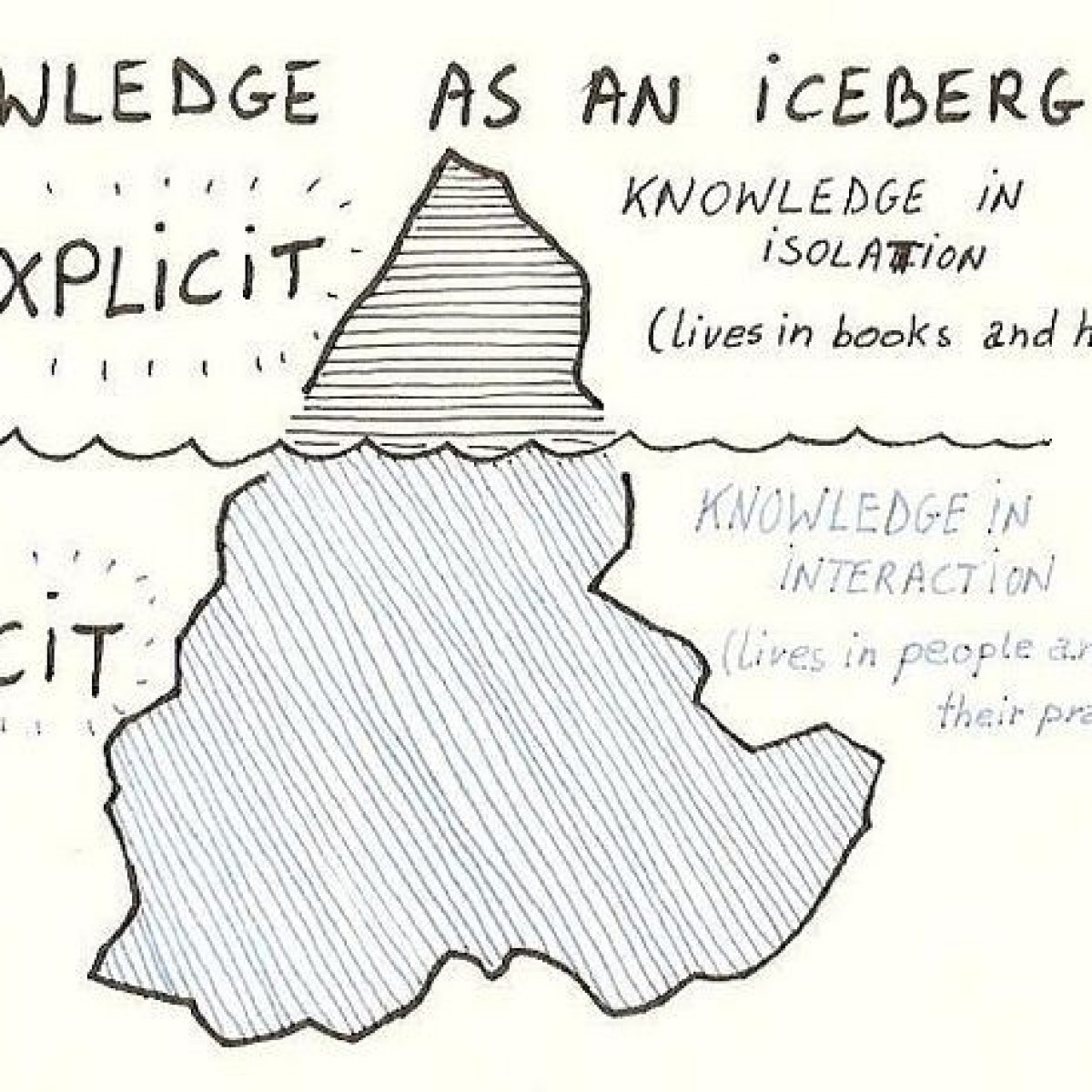Oleh: Adhy M. Nuur (Ketua LTN-NU Rancaekek)
Di negeri ini, bahkan adab bisa dijadikan bahan lelucon, asalkan dibungkus dengan narasi “investigasi.” Itulah pelajaran pahit yang baru saja diajarkan oleh Trans7 melalui program Xpose Uncensored. Dengan kamera yang lebih tajam dari pedang namun lebih serampangan dari logika, mereka menguliti kehidupan santri di Pondok Pesantren Lirboyo, bukan untuk memahami, tetapi untuk menghibur. Dalam tayangan itu, dengan nada sinis dan bumbu hiperbola, mereka mempertanyakan adab santri saat minum susu, “kok harus jongkok?” katanya. Sebuah pertanyaan yang sekilas tampak lucu, namun sesungguhnya menyingkap kebodohan epistemik yang dipoles menjadi hiburan. Ini bukan investigasi, melainkan sindiran rasa sinetron, dibungkus dengan moralitas yang setengah matang dan empati yang entah di mana ditaruhnya.
Ketika Adab dan Pesantren jadi Olokan
Program tersebut, yang menyorot kehidupan santri dan KH. Anwar Manshur, menampilkan pesantren seolah ruang yang asing, kolot, dan tak rasional. Mereka lupa bahwa adab bukanlah atraksi, melainkan jalan spiritual. Dalam tradisi pesantren, jongkok saat makan atau minum bukan simbol keterbelakangan, tapi wujud rendah hati, sebuah pelajaran batin yang menumbuhkan kesadaran bahwa bahkan segelas air pun tidak layak diminum dengan kesombongan. Tapi sayang, nilai sehalus itu tentu tidak cukup “klikbait” untuk mengisi prime time. Maka jadilah santri sebagai tontonan. Ironisnya, ketika negeri ini tengah dikepung isu korupsi, efisiensi, MBG, kegaduhan ijazah palsu, dan patologi birokrasi lainnya, kamera Xpose justru sibuk memelototi sendok santri. Begitulah, pengalihan isu kini tampil lebih teatrikal daripada sinetron Ramadan.
Segmen “Santrinya Minum Susu Aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan Pondok?” pada akhirnya bukan sekadar provokatif. Ia adalah satire yang salah sasaran, menusuk moral publik, bukan membuka mata penonton. Dalam ethics of care yang menjadi ruh tradisi Islam, tindakan sederhana seperti duduk ketika makan mencerminkan kesadaran akan keteraturan dan keadaban.
Banyak pihak, termasuk penulis, menilai bahwa tayangan tersebut melecehkan kiai serta lembaga pendidikan pondok pesantren. Penyajian kontennya bertendensi memojokkan kehidupan lingkungan pesantren sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman masyarakat. Narator dalam tayangan bahkan menambahkan komentar netizen (katanya) yang bagi banyak pihak, dianggap masuk kategori provokatif dan menghina: “Ketemu kiai nya masih ngesot dan cium tangan. Dan ternyata yang ngesot itulah yang ngasih amplop. Netizen curiga bahwa bisa jadi inilah kenapa sebagian kiai makin kaya raya.” Tidak cukup sampai di situ, pengisi suara pun menimpali dengan nada merendahkan: “Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit enggak sih?”
Narasi itu menegaskan tayangan tersebut tidak sekadar menyajikan fakta, tetapi menebar framing negatif dan prasangka terhadap kehidupan pesantren. Santri yang sejak kecil dididik dengan nilai ‘tawadhu’ (rendah hati) kini dipotret sebagai objek ejekan, kiai yang kharismatik dibingkai sebagai individu yang serakah. Dalam konteks ini, adab dan tradisi pesantren tidak lagi dihormati, melainkan disederhanakan menjadi bahan candaan untuk menarik perhatian pemirsa.
Tapi bagi industri televisi yang hidup dari rating, kearifan seperti itu tidak laku. Yang dijual adalah the exotic other. Maka pesantren pun direduksi jadi karikatur budaya, tempat yang dianggap lucu untuk ditertawakan oleh penonton urban yang kehilangan arah spiritual tapi masih ingin merasa lebih “modern”.
Kehilangan Ruh Jurnalisme
Namun yang lebih menyedihkan dari semua ini bukanlah tayangannya, melainkan kehilangan ruh jurnalisme itu sendiri. Dahulu, kita mengenal doktrin sakral: cover both sides. Prinsip yang dijunjung tinggi oleh setiap wartawan sejati, mendengar kedua pihak, menulis dengan adil, dan tidak menjustifikasi tanpa verifikasi. Kini, prinsip itu tinggal dekorasi di ruang redaksi, semacam kutipan etis yang dicetak besar di dinding kantor tapi diabaikan dalam setiap rapat redaksi. Dalam tayangan Xpose tersebut, kita tak melihat keseimbangan, apalagi klarifikasi. Yang tampak hanya satu sisi, kamera yang diarahkan tanpa tabayyun, tanpa empati, tanpa upaya memahami konteks sosial dan spiritual pesantren.
Di ruang redaksi modern, rating adalah Tuhan, dan empati hanyalah korban pertama. Dan siapa yang lebih aman untuk dikorbankan selain pesantren, institusi yang tidak punya buzzer, tidak punya iklan, dan tidak bisa membalas dengan press release berbayar? Mereka hanya punya kitab kuning, kesabaran, dan segelas susu yang diminum sambil jongkok, yang bahkan itu pun dijadikan bahan ejekan.
Fenomena ini sejatinya tidak berdiri sendiri. Edward S. Herman dan Noam Chomsky sudah lama menjelaskannya lewat konsep “manufacturing consent” bahwa media bukanlah cermin realitas, melainkan mesin pembentuk persepsi publik. Dalam sistem kapitalisme media, berita diseleksi, dikemas, dan diarahkan agar tetap sesuai dengan kepentingan pasar dan stabilitas kekuasaan.
Maka tak heran bila pesantren jadi sasaran empuk: mereka aman dikritik, tidak menimbulkan risiko politik, dan cukup eksotik untuk diviralkan. Di sisi lain, isu-isu besar yang mengancam elit kekuasaan justru diredam atau dialihkan melalui “drama kecil” seperti ini. Bila korupsi terlalu panas untuk diberitakan, munculkan saja isu ringan yang bisa menyedot emosi publik. Sorot kehidupan santri, buat narasi dramatis, tambahkan satire yang beringas, dan arahkan kamera ke tempat yang tidak akan mengancam siapa pun. Selesai. Rating naik, wacana publik pun tersesat.
UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan tegas mengamanatkan bahwa jurnalisme harus berkeadilan, berimbang, dan bertanggung jawab secara moral. Tapi pasal-pasal itu kini terdengar seperti ayat-ayat tua yang hanya dibaca saat ujian sertifikasi wartawan. Keadilan tidak menjual. Klarifikasi tidak viral. Dan santri yang jongkok minum susu? Nah, itu justru bisa dijadikan “pembuka” yang menggugah rasa ingin tahu publik urban yang haus sensasi budaya.
Ironi ini mengingatkan pada Imam al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin: “Rusaknya dunia karena rusaknya ulama dan rusaknya penguasa.” Jika beliau hidup hari ini, mungkin beliau akan menambahkan satu kategori lagi “dan karena rusaknya jurnalis.” Sebab ketika pena kehilangan adab, berita menjadi fitnah. Dan fitnah yang dibungkus dengan voice over dramatis jauh lebih berbahaya dari hoaks di media sosial. Ia merusak pelan-pelan, sambil tersenyum.
Ketika Media jadi Penghakim Moral
Pesantren sendiri, tentu bukan lembaga yang anti-kritik. Sejak abad ke-19, pesantren telah menjadi ruang dialektika sosial yang terbuka. Para kiai dan santri tidak alergi terhadap perbedaan pendapat. Mereka membaca Ibn Khaldun, al-Ghazali, dan Nurcholish Madjid dengan semangat ilmiah yang tinggi. Tapi kritik yang sehat berbeda dengan penghinaan yang disamarkan. Kritik yang Islami mengandung niat islah, niat memperbaiki, bukan mempermalukan. Kritik adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar, tapi bila dilakukan tanpa adab, ia berubah menjadi munkar itu sendiri.
Sayangnya, media hari ini lebih sibuk menjadi penghakim moral ketimbang pencari makna. Dalam ruang redaksi yang dikuasai rating, “narasi keadilan” hanya berlaku jika menguntungkan engagement. Kamera diarahkan bukan ke penderitaan rakyat kecil, tetapi ke tempat yang bisa menghasilkan sensasi. Maka jangan heran bila kamera lebih suka merekam santri minum susu sambil jongkok ketimbang pejabat makan uang rakyat sambil tertawa.
Padahal, pesantren adalah laboratorium moral bangsa. Di sana, nilai-nilai kesabaran, tawadhu’, dan tanggung jawab sosial diajarkan bukan lewat teori, tapi lewat teladan. Setiap gerak, dari cara berpakaian hingga cara makan, memiliki makna spiritual. Dalam perspektif ta’dib yang dirumuskan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, adab adalah kesadaran akan tempat segala sesuatu, termasuk diri manusia di hadapan Tuhan. Maka ketika santri diajarkan minum sambil duduk atau jongkok, itu bukan sekadar etiket, melainkan latihan spiritual: agar manusia tidak serakah, agar ia sadar bahwa segala nikmat berasal dari Allah SWT, bukan dari dirinya sendiri. Dan ketika memberikan amplop sambil “ngesot” dan cium tangan di-framing sebagai manifestasi keserakahan kiai, tanpa mengetengahkan investigasi apa maksud dan tujuan memberi amplop itu?
Tapi semua itu tak terlihat dalam kamera modern yang hanya bisa merekam, tapi tak mampu memahami. Kamera hanya menangkap bentuk, bukan makna. Itulah tragedi media hari ini: mereka merekam cahaya, tapi kehilangan nur.
Di titik ini, kita harus bertanya: apakah jurnalisme kita masih punya ruh tabayyun?
“Tabayyunlah ketika datang kepadamu berita, agar kamu tidak menyesal.” (QS. Al-Hujurat: 6). Ayat ini seharusnya menjadi prinsip dasar setiap wartawan Muslim. Namun dalam praktiknya, verifikasi kini kalah cepat dari rating. Sementara tabayyun dianggap tidak produktif karena memakan waktu. Maka lahirlah berita-berita setengah matang, penuh insinuasi, tapi diklaim sebagai “investigasi.”
Namun, kebenaran tidak akan lapuk meski ditimbun oleh kebisingan dunia. Pesantren akan tetap hidup, meski beberapa oknum mencoba menertawakannya. Karena pesantren tidak tumbuh dari popularitas, tapi dari keikhlasan. Tidak dibangun dari algoritma, tapi dari doa. Dan selama masih ada santri yang mengaji dan mempraktikan adab akhalul karimah, pesantren akan tetap menjadi benteng moral yang tak bisa diruntuhkan oleh kamera sebesar apa pun.
Mungkin sudah waktunya media belajar kembali kepada pesantren. Belajar tentang kesabaran dalam mencari fakta, tentang adab sebelum bicara, tentang keberanian menyampaikan kebenaran tanpa menghina. Karena di zaman ketika semua orang ingin berbicara, mereka salah satunya yang masih punya adab yang akan didengar.
Jika media tak lagi mampu menampilkan wajah pesantren dengan adil, biarlah pesantren yang menulis narasi mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa menulis sejarah tanpa perlu headline. Dengan tinta yang jujur, dengan bahasa yang lembut, dan dengan akhlak yang tidak bisa dijual di jam tayang prime time. Karena dalam dunia yang semakin bising oleh opini dan distorsi, hanya hati yang bersih yang bisa menyampaikan kebenaran.
Jika kamera tak mampu melihat itu, maka biarlah ia ditutup, bukan demi sensor, tapi demi akal sehat bersama. Karena ketika adab dijadikan bahan lelucon, yang sebenarnya runtuh bukan pesantren, melainkan martabat jurnalisme itu sendiri.
Dari Investigasi ke Inve-Stigma-Si
Kasus Xpose Uncensored jadi contoh sempurna bagaimana investigasi bisa menjelma menjadi inve-stigma-si, seni menyelidiki dengan niat bukan mencari kebenaran, tapi mencari masalah.
Tayangan yang seharusnya membuka wawasan tentang kehidupan pesantren justru membuka luka sosial. Kamera diarahkan ke wajah santri yang hormat kepada kiai, tapi narasinya seolah menyebut: “Tradisi ini perlu dikaji ulang.” Narasi satu arah, framing sepihak, dan potongan gambar dipoles seperti trailer film kriminal seolah dunia pesantren adalah lembaga misterius yang perlu diselidiki bak sindikat rahasia.
Tak heran publik murka. Layar dunia maya pun disesaki oleh hashtag: #BoikotTrans7. Ironisnya, yang diboikot bukan hanya stasiun televisi, tapi juga kepercayaan publik terhadap jurnalisme itu sendiri. Karena ketika wartawan kehilangan empati, ia bukan lagi penyampai kabar, melainkan pembentuk stigma.
Efek dari inve-stigma-si bukan sekadar trending di Twitter dan berbagai media sosial lainnya, tapi juga luka sosial yang nyata. Santri yang semula bangga dengan almamaternya, kini takut disorot kamera. Kiai yang dulu dihormati, kini disangka pengusaha rohani. Tradisi yang sakral dijadikan montase humor nasional.
Dan yang paling ironis, semua dilakukan atas nama “pencerahan publik”. Padahal, pencerahan tanpa empati hanyalah sorot lampu yang menyilaukan. Ia tidak membuka mata, tapi membutakan nurani.
Jurnalisme, sejatinya, adalah cermin masyarakat. Tapi ketika cermin itu retak oleh sensasi, yang terpantul bukan lagi kebenaran,melainkan wajah cacat persepsi. Tayangan yang katanya “membuka mata publik” justru menutup hati banyak orang.
Mungkin para wartawan lupa bahwa setiap potongan video adalah potongan harga moral. Bahwa setiap suara narator bisa jadi doa atau dosa. Bahwa mikrofon tidak hanya merekam suara, tapi juga menciptakan makna.
Expose berarti membuka. Tapi ex-pos berarti kehilangan posisi, kehilangan tempat berpijak. Ketika media lebih sibuk menuding daripada memahami, maka yang hilang bukan hanya reputasi stasiun televisi, tapi juga makna luhur dari profesi jurnalis. Karena hari ini, yang paling sulit bukan mencari berita, tapi menjaga kebenaran agar tidak tergelincir jadi bahan bakar trending topic.
Bangkitnya Citizen Accountability
Di era digital seperti sekarang, batas antara produsen dan konsumen informasi kian kabur. Media tidak lagi menjadi satu-satunya penjaga gerbang informasi. Kini, publik punya ruang yang luas untuk menyuarakan kritik, melakukan koreksi, bahkan mengorganisasi tekanan sosial terhadap lembaga-lembaga media. Ketika Trans7 diserbu kritik tajam dan tagar #BoikotTrans7 menggema di jagat maya, itu bukan sekadar ekspresi kemarahan spontan semata, melainkan sinyal kuat bahwa publik mulai memainkan peran barunya: sebagai pengawas media. Inilah bentuk konkret dari citizen accountability, atau akuntabilitas yang lahir dari warga.
Dulu, media kerap diasumsikan sebagai institusi yang sakral dan tak tersentuh. Namun kini, ketika publik bisa membandingkan narasi dari berbagai sumber, membongkar bias, dan menelusuri motif tersembunyi di balik berita, media pun tak lagi kebal. Kesalahan redaksional, framing yang menyudutkan kelompok tertentu, hingga ketidakseimbangan narasi bisa langsung dipantau dan dikritik secara terbuka.
Namun di tengah kebangkitan suara publik ini, muncul satu kebutuhan mendesak: literasi media. Kita tidak hanya memerlukan publik yang vokal, tetapi juga publik yang cerdas secara kritis. Tak semua yang viral itu benar. Tak semua yang ramai itu adil. Ketika satu tayangan menyudutkan lembaga sosial atau komunitas tertentu, publik perlu bertanya:
• Siapa yang diuntungkan dari narasi ini?
• Apakah ini kritik objektif, atau bagian dari agenda tersembunyi?
• Apa yang tidak ditampilkan dalam tayangan ini, dan mengapa?
Sebab dalam banyak kasus, yang tidak diberitakan justru lebih penting dari yang ditayangkan. Ketimpangan informasi menciptakan bias persepsi. Di sinilah literasi media berperan sebagai alat navigasi: bukan sekadar untuk membaca berita, tapi untuk membongkar kepentingan di balik berita.
Tagar #BoikotTrans7 adalah bukti bahwa kesadaran publik belum mati. Tapi perlu kita sadari, boikot tidak boleh berhenti pada reaksi emosional. Ia perlu diolah menjadi gerakan etik dan strategis, melalui tuntutan klarifikasi terbuka, desakan permintaan maaf publik, hingga advokasi pembentukan mekanisme kontrol internal seperti ombudsman publik. Jika media tidak mampu atau tidak mau memperbaiki diri dari dalam, maka masyarakat punya hak dan tanggung jawab untuk mengontrolnya dari luar.
Literasi dan Rekonsiliasi
Kita tengah menyaksikan transisi penting: dari masyarakat yang dulunya pasif mengonsumsi berita, menjadi masyarakat yang aktif memverifikasi, mengkritisi, bahkan mengoreksi. Fenomena ini menandai pergeseran peran masyarakat dari consumers of information menjadi guardians of truth. Tapi tentu, kekuatan ini tidak bisa dijalankan tanpa pondasi yang kuat: literasi kritis.
Literasi kritis bukan berarti sinis terhadap semua media. Bukan pula menolak semua berita yang tak sesuai dengan keyakinan kita. Literasi kritis adalah kemampuan untuk membaca dengan sadar, membedakan antara fakta dan opini, serta menyadari bahwa setiap media punya kepentingan tertentu. Ini yang menjadi kunci agar protes publik tidak berubah menjadi pembajakan narasi oleh kelompok tertentu.
Sayangnya, ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap media arus utama, mereka sering beralih ke sumber-sumber alternatif: media warga, saluran dakwah, hingga media partisan. Ini bukan sepenuhnya salah, namun jika tidak dibarengi dengan kesadaran kritis, kita justru berpindah dari satu bias ke bias yang lain.
Krisis kepercayaan terhadap media dapat memperbesar polarisasi sosial. Sebagian publik mulai melihat media sebagai alat propaganda anti-Islam atau anti-rakyat. Di sisi lain, sebagian jurnalis dan pengamat media menganggap kritik publik sebagai bentuk anti-kritik atau serangan terhadap kebebasan pers. Dua kubu ini sama-sama keliru jika tidak mau membuka ruang dialog.
Yang kita butuhkan bukan saling serang, tapi rekonsiliasi antara moral dan profesionalisme. Jurnalisme yang sehat adalah jurnalisme yang berpijak pada etika, kejujuran, dan keberpihakan kepada kebenaran, bukan kepada kekuasaan atau pasar. Sementara publik, harus belajar menjadi konsumen media yang aktif, cerdas, dan bertanggung jawab.
Kontrol sosial terhadap media bukan bentuk pelanggaran kebebasan pers, justru sebaliknya, itu adalah bagian penting dari demokrasi. Ketika media menyimpang dari fungsinya sebagai penyampai kebenaran, masyarakat harus hadir sebagai korektor. Namun koreksi publik akan menjadi produktif hanya jika disertai dengan pemahaman, etika, dan strategi.
Era digital memberi kita kekuatan yang belum pernah ada sebelumnya. Tapi seperti semua kekuatan, ia datang bersama tanggung jawab. Maka mari jaga kekuatan itu dengan literasi, bukan sekadar emosi.