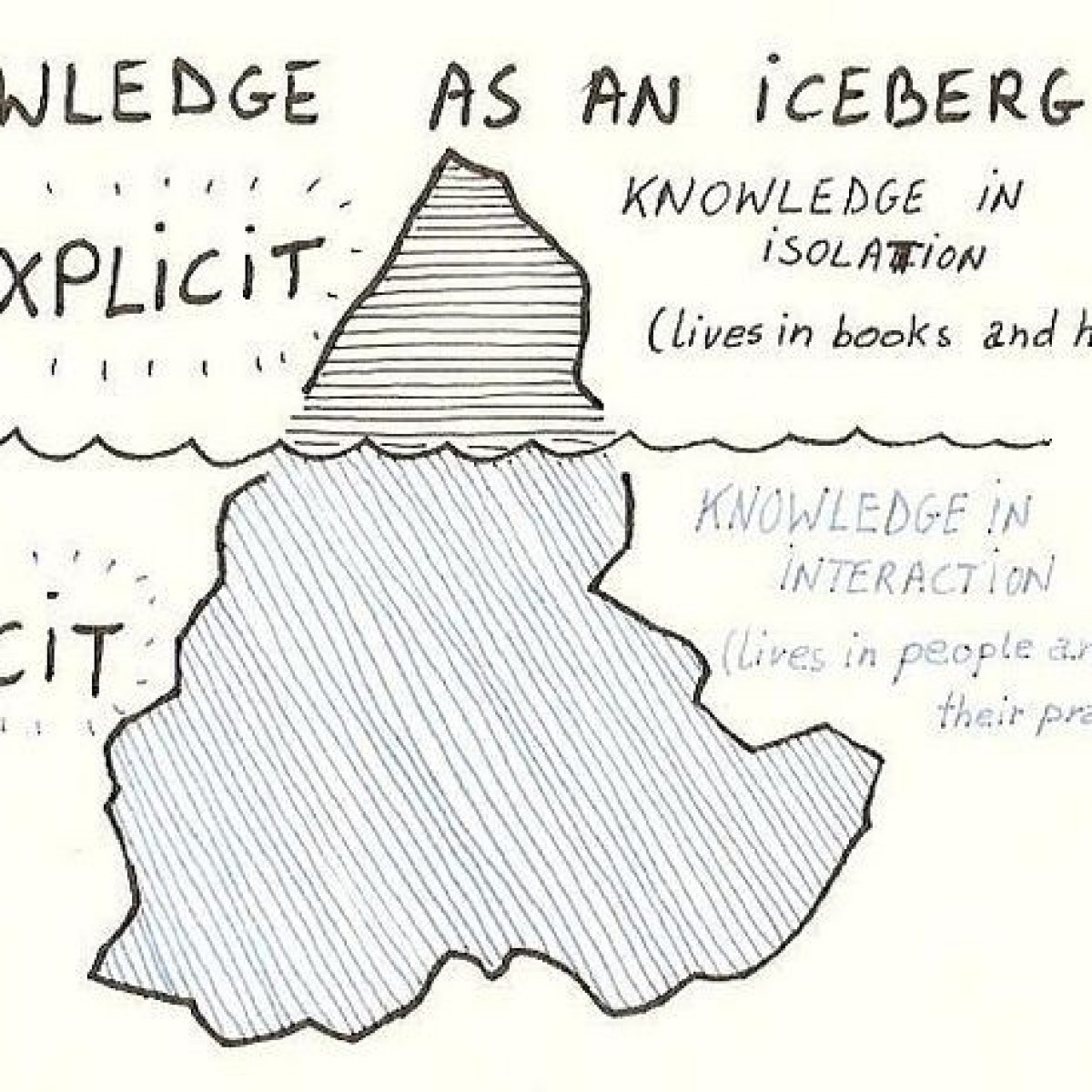Oleh : Adhy M. Nuur
Di zaman sekarang, melakukan kesalahan di ruang publik itu rasanya seperti main petak umpet di lapangan yang disiram matahari tengah hari. Mau sembunyi di balik apa? Tiang bendera? Pohon kering? Percuma, karena begitu kita lengah sedikit saja, dunia langsung cekrek–rekam–unggah. Kamera bukan lagi benda; ia sudah jadi spesies baru yang berkembang biak tanpa lelah: CCTV, dashcam, atau HP orang lewat.
Ekosistem digital membentuk lanskap baru: kesalahan kecil bisa bermigrasi menjadi pertunjukan nasional. Atau bahkan internasional kalau algoritma sedang iseng. Ini sejalan dengan konsep “networked publics” dari Danah Boyd (2010), di mana ruang sosial tercipta dan diperluas oleh teknologi jaringan. Artinya, segala yang tadinya cukup diselesaikan lewat permintaan maaf di beranda rumah atau di warung kopi, kini tiba-tiba bisa menjadi bahan perdebatan nasional, lengkap dengan analis dadakan dan opini pakar dadakan.
Dan seterusnya kita sudah hafal: netizen datang seperti arus pasang. Bukan pelan, langsung melabrak pantai. Ada yang tulus ingin memahami konteks, tapi banyak juga yang komentar seperti mesin slot sosial: tarik tuas, keluar komentar acak, kadang bijak, kadang pedas, kadang cuma emot marah tanpa sebab. Fenomena ini disebut “digital vigilantism” oleh Trottier (2017), kecenderungan warga digital menjadi polisi sosial tanpa badge, tanpa SOP, tapi penuh kecepatan dan keyakinan.
Kita hidup dalam era di mana opini tercepat sering dianggap opini paling benar, bukan karena kualitasnya, tapi karena sinyal 5G-nya lebih stabil, bahkan sudah lebih cepat di jaringan 1,4 Ghz. Viralnya sebuah video atau foto membuat banyak orang lupa bahwa rekaman kamera itu cuma satu fragmen kecil dari hidup seseorang, fragmen yang sering tidak lengkap, tidak berimbang, dan kadang tidak mewakili sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Studi media menyebut ini “context collapse” (Marwick & boyd, 2011): berbagai audiens, norma, dan interpretasi melebur menjadi satu, lalu meledak dalam bentuk komentar dan penghakiman massal.
Untuk menambah bumbu, algoritma ikut menyulap drama kecil menjadi trending topic. Bukan karena ia peduli etika, tapi karena apa yang diinterpretasi Zuboff (2019) mengarah ke “engagement equals profit”. Jadi kalau ada keributan, algoritma akan merayu semua orang: “Hei, mau lihat drama baru?” Dan kita, sebagai manusia yang mudah tergoda seperti melihat gorengan baru keluar wajan, sering meng-klik tanpa mikir jauh.
Netizen lalu merasa punya legitimasi moral untuk menegur, menasihati, atau bahkan menghukum secara digital. Padahal, ironisnya, tidak ada orang yang benar-benar kebal dari kesalahan. Semua punya potensi jadi “pemeran utama” dalam drama publik berikutnya. Kita hanya berharap semoga tidak ada kamera yang aktif saat itu terjadi. Tapi harapan tinggal harapan, kamera lebih setia daripada mantan.
Netizen dan Kebiasaan Memviralkan: Fenomena Latah Kolektif
Di dunia yang bergerak secepat scroll jempol, orang sekarang berlomba-lomba jadi yang paling duluan membagikan sesuatu. Begitu ada video jatuh dari motor, sedikit cekcok di minimarket, atau drama level receh yang dulu hanya jadi gosip warung bakso, mendadak berubah menjadi komoditas digital. Netizen pun segera menyiapkan jempol, caption pedas, dan komentar penuh tenaga dalam.
Fenomena “viralkan dulu, mikirnya nanti” ini bukan saja khas Indonesia; ini wabah global yang merayap seperti notifikasi yang tak pernah tidur. Riset dari Brandwatch (2025) menunjukkan betapa kuatnya dorongan FOMO (fear of missing out): orang takut ketinggalan trending tertentu, ikut merek tertentu, cerita, takut tidak dianggap update, atau sekadar ingin terlihat jadi bagian dari keramaian digital. Dalam bahasa sederhana: kalau semua orang ngomongin itu, masa kita diam?
Dari sinilah lahir yang saya sebut, dengan nada geli, latah digital. Semacam reflek sosial baru: yang penting share dulu, soal benar–salah belakangan. Fenomena ini berkaitan dengan apa yang disebut dalam kajian media sebagai “participatory culture” (Jenkins, 2006). Teknologi memberi ruang bagi siapa pun untuk ikut serta dalam percakapan publik, tapi partisipasi yang lahir tidak selalu matang. Banyak yang datang bukan karena peduli isu, melainkan karena butuh panggung, meski panggungnya sekadar kolom komentar.
Apalagi algoritma platform bekerja seperti pawang masa yang terlalu semangat: apa pun yang ramai akan terus diangkat ke permukaan. Drama kecil di sudut kota bisa berubah menjadi gelombang nasional karena mesin digital merasa dunia butuh tontonan baru. Dan manusia, seperti biasa, gampang terpanggil. Kita senang berada “di tengah pusaran”, walaupun sebenarnya hanya numpang lewat.
Dalam konteks sosial digital, perilaku latah ini diperkuat oleh “bandwagon effect”, kecenderungan ikut arus karena semua orang tampak melakukan hal yang sama (Bindra et al., 2022). Maka tak heran, sebuah postingan yang awalnya sepi tiba-tiba meledak, bukan karena isinya penting, tapi karena ritme sosial mendorong orang untuk mengikuti keramaian.
Latah digital juga memunculkan efek samping: kaburnya batas antara informasi dan impulsif. Banyak orang lupa mengecek validitas, lupa menahan diri, lupa bertanya: “Ini bener nggak sih?” Yang penting dapat kesempatan komentar, seperti pemain cadangan yang tiba-tiba dipanggil masuk lapangan, panik, tapi tetap tampil.
Padahal, dalam kajian etika media, tindakan memviralkan tanpa jeda ini berisiko menimbulkan “digital harm”, mulai dari salah paham, stigma, hingga persekusi digital. Namun dunia maya jarang memberi ruang untuk jeda. Kita sering dikejar perasaan bahwa isu harus dikomentari sekarang atau hilang selamanya.
Pada akhirnya, kita semua jadi bagian dari orkestra latah kolektif: ramai, gaduh, penuh semangat, tapi sering tanpa arah. Dan mungkin, di antara keributan itu, kita lupa satu hal sederhana: tidak semua hal wajib menjadi konsumsi publik. Tidak semua drama perlu terang benderang. Dan tidak semua video layak menjadi bahan hiburan nasional.
Kadang, dunia butuh sedikit hening. Atau sedikit jeda. Jeda untuk berpikir. Jeda untuk tidak latah.
Demokrasi Netizen dan Budaya Menghakimi
Di Indonesia, kita hidup dalam apa yang sering saya sebut sebagai “demokrasi netizen”, sebuah ruang publik digital tempat siapa pun boleh bersuara: protes, kritik, marah, bercanda, atau ngasih opini sambil kunyah bala-bala (bakwan) yang terlalu berminyak. Ini, kalau dipikir, adalah wujud paling liar dari gagasan ruang publik ala Habermas (1991): ruang di mana warga mengolah opini, berdebat, dan menyuarakan pandangan.
Secara teori, ruang publik itu mulia. Tetapi internet berhasil mengubahnya menjadi “pasar malam” yang buka 24 jam: ramai, penuh suara, penuh warna, dan kadang tidak jelas siapa yang sebenarnya sedang bicara dengan siapa.
Masalah serius muncul ketika opini berubah menjadi penghakiman massal.
Seseorang salah sedikit → diseret rame-rame → divonis tanpa proses → ditinggal tanpa tanggung jawab.
Dulu, kalau ada orang melakukan kesalahan kecil, masyarakat sekitar mungkin hanya menggerutu atau menasihati. Sekarang? Kesalahan itu bisa berubah menjadi tontonan nasional. Warga digital beramai-ramai merasa punya mandat untuk mengadili, lengkap dengan ketua majelis komentar, jaksa kolom balasan, dan hakim share button.
Fenomena ini menurut para peneliti disebut trial by social media, pengadilan versi dunia maya yang tidak mengenal praduga tak bersalah. Dalam riset Maddox et al. (2019) di New Media & Society, tekanan publik di internet bisa menciptakan apa yang disebut “instant public justice”, sebuah keadilan instan yang sifatnya ambigu: kadang mengenai sasaran, tapi sering juga membabi buta.
Dalam logika algoritma, kemarahan adalah bahan bakar. Dan ketika ribuan suara muncul tanpa konteks, tanpa data, tanpa jeda, kita terperosok ke jurang tempat emosi lebih kuat daripada fakta. Para psikolog menyebut ini sebagai moral outrage amplification, kemarahan moral yang diperbesar sistemik oleh platform (Brady et al., 2017). Jadinya, satu kesalahan kecil bisa membengkak seperti balon yang dipompa tanpa henti.
Ironisnya, demokrasi netizen sering merasa sedang menegakkan keadilan, padahal yang terjadi kadang hanya pelampiasan kolektif. Ada kepuasan aneh di balik memberi komentar pedas, semacam sensasi “aku lebih bermoral dari kamu”, padahal orang tersebut mungkin cuma lagi bad day atau salah ucap.
Sementara itu, orang yang jadi target penghakiman massal tidak selalu diberi ruang menjelaskan. Context collapse, fenomena di mana satu potongan video menghapus semua konteks (Marwick dan Boyd, 2011), membuat seseorang bisa divonis hanya berdasarkan 10 detik rekaman yang belum tentu mewakili kenyataan.
Jadi, walaupun demokrasi netizen memberi ruang bersuara, ia membawa risiko bawaan:
ketika kebebasan bercampur impuls, lahirlah kerumunan yang menghakimi. Dan kerumunan digital itu tidak punya tombol “undo”. Begitu viral, begitu pula bekasnya.
Yang membuat keadaan semakin rumit adalah: tidak ada SOP untuk jadi netizen. Tidak ada pelatihan etika sebelum masuk media sosial. Tidak ada modul “bagaimana mengkritik tanpa membunuh karakter orang”. Kita semua masuk ke dunia digital tanpa pedoman; akibatnya, ruang publik yang ideal berubah menjadi gelanggang yang penuh suara, tapi minim kebijaksanaan.
Pada akhirnya, ini bukan tentang membungkam suara publik. Justru sebaliknya:
kita perlu merawat agar ruang publik tidak berubah menjadi ruang penghakiman.Karena kalau semua orang sibuk menghukum, tidak ada lagi yang benar-benar mendengar.
Post-Truth: Ketika Kebenaran Dikalahkan Perasaan
Setelah melewati huru-hara “viralkan dulu, pikir nanti” dan “demokrasi netizen yang doyan menghakimi”, kita masuk ke level permainan yang lebih rumit: era post-truth. Di tahap ini, kebenaran itu mirip mie instan: fleksibel, bisa dikreasikan sesuai selera, dan gampang diseduh sesuai selera emosional audiens.
Menurut Oxford Dictionary (2010), post-truth adalah kondisi ketika fakta objektif kalah pengaruh dibanding opini yang bersandar pada emosi dan keyakinan personal. Artinya, yang menang bukan data, tapi perasaan; bukan bukti, tapi “aku ngerasa ini benar.”
Di era ini, informasi tidak lagi berjalan lurus. Ia berputar seperti kipas angin yang baling-balingnya dipasang miring:
Versi A muncul duluan dan viral karena timingnya oke. Versi B hadir belakangan, membantah, tapi audiens sudah keburu jatuh hati pada Versi A. Lalu, versi C diproduksi akun lain, kadang benar, kadang ngawur, untuk memperkuat narasi mana pun yang paling sesuai dengan preferensi kelompoknya.
Hasilnya? Kebenaran punya banyak versi. Seolah-olah kita sedang menonton film multiverse, cuma lebih berantakan dan penuh komentar “fix ini salah satu pihak pasti salah”.
Fenomena ini sudah lama diperingatkan oleh McIntyre (2018) dalam bukunya Post-Truth. Ia menulis bahwa masyarakat makin cenderung memilih “kebenaran yang enak di hati”, kebenaran yang memberi rasa nyaman, validasi, dan cocok dengan identitas kelompok, meskipun itu bukan versi yang paling akurat. Kita memilih cerita seperti memilih baju: yang pas, yang sesuai gaya, bukan yang paling mendekati kenyataan.
Dalam kajian komunikasi, ini diperkuat oleh confirmation bias, kecenderungan menyukai informasi yang sesuai pendapat sendiri (Nickerson, 1998). Jadilah kolaborasi memabukkan antara: algoritma yang memberi kita apa yang ingin kita dengar, emosi yang bergerak lebih cepat dari nalar, dan kultur digital yang lebih menghargai kecepatan ketimbang ketepatan.
Dampaknya, ruang digital berubah jadi pasar kebenaran. Semua orang jualan perspektif. Yang paling heboh yang paling laris. Yang paling logis? Seringnya malah tenggelam di antara komentar yang teriak lebih keras.
Post-truth membuat perdebatan publik tidak lagi mencari jawaban, tapi mencari sekutu emosional. Orang berbicara bukan untuk memahami, melainkan untuk menang. Bukan untuk berdiskusi, tapi untuk memastikan bahwa “versiku paling benar karena cocok dengan rasa di dadaku.”
Dan ironisnya, di tengah kebingungan multiverse kebenaran ini, kita lupa satu hal sederhana: kebenaran tidak peduli perasaan kita. Tapi dunia digital modern terlalu nyaman untuk membiarkan fakta bekerja sendirian. Kita sering lebih percaya video yang sudah dibumbui caption dramatis ketimbang laporan resmi. Kita lebih percaya thread panjang penuh emosi daripada analisis yang datanya lengkap. Di sinilah post-truth menjadi jebakan: ia memanjakan kita, tetapi menyesatkan arah kompas berpikir.
Akhirnya, bukan kebenaran yang menjadi tujuan, tapi validasi. Dan begitu validasi menjadi sumber kebenaran, debat berubah menjadi ritual emosional, bukan percakapan rasional.
Manfaatnya Netizen Beropini, Tapi Lebih Baik Diselidiki Dulu
Berdiskusi itu kegiatan favorit umat online. Semua orang pernah, bahkan sering, jadi komentator dadakan. Kadang sambil rebahan, kadang sambil nyuap mi instan, kadang sambil nunggu laundry selesai.
Kita familiar dengan kalimat-kalimat sakral netizen: “Menurut saya sih…” “Kayaknya dia salah, deh…” “Kalau gue jadi dia, pasti nggak gitu dong…” Dan ini normal. Bahkan sehat. Dalam teori demokrasi deliberatif, suara warga, meski serampangan sekalipun, adalah bagian dari mesin sosial (Habermas, 1991; Dahl, 1998). Ruang publik digital memang tempat kita belajar bersuara, berdebat, dan berlatih menjadi manusia yang berpikir.
Tapi masalah muncul ketika opini yang mestinya lentur berubah menjadi batu bata.
Keras. Kaku. Dan dilempar ke mana saja. Makanya, akan jauh lebih sehat kalau kita mulai membudayakan beberapa kebiasaan kecil yang terdengar sederhana tetapi menyehatkan nalar:
Pertama, opini muncul setelah sedikit cek fakta. Nggak harus kayak jurnalis investigatif yang nguntit data sampai subuh. Cukup cek sumber, baca konteks, lihat timeline, tanya: “Ini masuk akal nggak?” Itu saja sudah membuat komentar kita naik satu level dari “impulsif” ke “bertanggung jawab”. Kedua, beri ruang untuk kemungkinan salah.
Dunia digital sering menuntut kepastian. Padahal hidup, bahkan martabak pun, tidak selalu pasti. Mengakui bahwa kita bisa salah bukan tanda kelemahan, justru bentuk kecerdasan kognitif. Ketiga, siap meralat pendapat kalau informasi baru muncul. Budaya “oh ternyata saya salah ya, saya kira begini” adalah vitamin otak yang hilang dari internet.
Seolah-olah mengubah pendapat adalah kehinaan, padahal itu gejala orang dewasa yang otaknya masih lentur.
Fenomena keras kepala digital ini ada penjelasan ilmiahnya. Menurut riset MIT oleh Vosoughi et al. (2018), berita palsu, terutama yang emosional, menyebar jauh lebih cepat daripada berita benar. Alasannya sederhana: narasi yang membakar perasaan lebih memikat daripada akurasi yang kalem. Artinya, kehati-hatian bukan sekadar sopan santun.
Ia adalah mekanisme pertahanan otak di ekosistem informasi yang selalu haus sensasi.
Di internet, kecepatan sering mengalahkan ketepatan. Emosi sering mengalahkan logika. Dan komentar spontan sering terdengar lebih meyakinkan daripada analisis yang pelan-pelan dibangun. Maka, kalau bisa berhenti sejenak sebelum mengetik opini, itu bukan memperlambat demokrasi. Itu justru menunjukkan kedewasaan digital , semacam versi modern dari menahan diri sebelum menambahkan sambal ekstra yang kita tahu akan bikin perut berontak besok pagi.
Kita tetap bisa beropini, tetap bisa berceloteh, tetap bisa “ngomong yang kita pikirkan”, tapi dengan modal sedikit kehati-hatian. Karena kehati-hatian itulah yang membuat ruang digital tidak berubah menjadi arena salah paham massal. Pada akhirnya, opini adalah hak.
Tapi kualitas opini adalah pilihan.
Dari Viral Culture ke Tarbiyah Digital: Bagaimana Islam Mengajarkan Kita Menyikapi Semua Ini
Segala fenomena yang kita bahas, budaya latah digital, demokrasi netizen yang menghakimi, post-truth yang membengkokkan fakta, hingga hidup orang hancur karena viral, sebenarnya punya cermin yang sangat jelas dalam ajaran Islam. Bahkan ribuan tahun sebelum media sosial muncul, Islam sudah menyiapkan sistem nilai yang terasa seperti antivirus spiritual untuk dunia digital yang bising ini.
Pertama, “Tahan jempol sebelum share”; adalah perintah langsung Al-Qur’an. Fenomena FOMO, latah digital, dan “share dulu, fakta belakangan” bertentangan dengan adab paling dasar dalam Islam: tabayyun. Allah menegaskan: “Jika datang kepada kalian suatu berita dari orang fasik, maka telitilah (tabayyun)…” (QS. Al-Hujurat: 6). Ayat ini seperti poster besar di depan pintu dunia maya: stop, cek dulu, jangan sembarang sebar. Dalam tarbiyah, ini adalah pelajaran awal tentang tsiqah (kepercayaan), amanah, dan memelihara stabilitas sosial. Viral tanpa verifikasi sering menimbulkan fitnah; dan fitnah, kata Nabi, lebih besar dosanya dari pembunuhan (QS. Al-Baqarah: 191). Jadi sebenarnya, “tahan jempol beberapa detik” itu bukan sekadar tips literasi digital. Itu ibadah kecil, bentuk ketaatan pada prinsip tabayyun yang sangat fundamental.
Kedua, budaya menghakimi adalah lawan dari akhlak; dalam Islam, memberi nasihat itu mulia. Tapi menghakimi? Itu daerah rawan dosa. Allah memperingatkan dengan sangat tegas: “Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa.” (QS. Al-Hujurat: 12). Fenomena trial by social media, cancel culture, dan pengadilan tanpa proses dalam dunia maya sering lahir dari su’uzhan kolektif, praduga buruk yang dipercaya ramai-ramai. Padahal dalam tarbiyah, kita diajarkan bahwa seorang mukmin adalah: tadzakkar (mudah mengingat nilai), tawaadhu’, sabar, dan lembut dalam menegur. Menghancurkan karakter seseorang karena 10 detik video bukan teguran islami.
Itu zalim digital.
Ketiga, post-truth; ketika kebenaran dikalahkan perasaan, Islam sudah memberi peringatan lama. Post-truth adalah kondisi di mana perasaan lebih dipercaya daripada fakta.
Namun Islam sudah menegur: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8). Ini luar biasa relevan. Di timeline media sosial: kalau kita suka seseorang → narasi apa pun terasa benar. kalau kita tidak suka seseorang → kritik apa pun terasa salah. Sedangkan Islam mengajarkan standar yang lebih tinggi: kebenaran tidak boleh tunduk kepada emosi. Adil itu bukan soal rasa nyaman, tapi tentang amanah menegakkan fakta.
Kelima, “Kamera tidak netral”; sejalan dengan prinsip “jangan lihat hanya dengan zahir”. Islam mengingatkan bahwa manusia mudah tertipu oleh tampilan luar. Nabi ﷺ berkata: “Cukuplah seseorang dianggap berdosa jika ia menceritakan semua yang ia dengar.” (HR. Muslim). Potongan video yang viral hanyalah “apa yang tampak”, bukan “apa yang terjadi”. Adab tarbiyah mengajarkan: lihat konteks, bukan sekadar konten. Nilai dengan hati yang bersih, bukan dengan amarah yang liar.
Kelima, ketika hidup seseorang hancur karena viral; Islam meminta kita untuk melindungi, bukan mempermalukan. Dari perawat joget, ibu-ibu sesajen, pegawai SPBU, guru honorer, hingga drama tumbler, semuanya memperlihatkan satu hal: viral bisa menghancurkan lebih keras daripada kesalahannya. Dalam Islam, menghancurkan kehormatan seseorang adalah dosa besar. Nabi ﷺ bersabda: “Setiap Muslim atas Muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Itu berarti kehormatan digital pun wajib dijaga. Seseorang boleh salah, tapi Islam mengajarkan islah, bukan exposure; taubat, bukan trial by timeline.
Keenam, dalam tarbiyah, refleksi diri lebih utama daripada berburu kesalahan orang lain; budaya viral membuat kita fokus ke salah orang. Padahal tarbiyah mengajarkan:
islah diri lebih utama daripada sibuk menilai orang. Umar bin Khattab pernah berkata:
“Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab.” Di dunia media sosial, ini bisa diterjemahkan menjadi: → cek dulu niat sebelum berkomentar → timbang dulu manfaat sebelum membesarkan masalah → utamakan memperbaiki diri daripada mempermalukan orang lain
Jadi, bagaimana seharusnya Muslim bermedia sosial? Ringkasnya, begini narasi tarbiyah digital yang sejalan dengan Al-Qur’an dan Sunnah: 1) Tabayyun sebelum share.
Kalau ragu → tunda. Kalau belum jelas → diam. Diam itu pilihan etik dalam Islam; 2) Jangan menghakimi dari potongan video. Lihat dari sisi kasih sayang, bukan dari murka; 3) Beri ruang orang lain bertobat, klarifikasi, dan memperbaiki diri. Allah saja membuka pintu taubat setiap saat , masa kita menutup pintu maaf begitu cepat? 4) Biasakan berkata: “Oh, saya salah.”
Ini adab penting dalam tarbiyah: tawadhu’ dalam ilmu dan pendapat; 5) Jaga kehormatan orang lain seperti menjaga kehormatan sendiri. Ini inti akhlak Islam: rahmah, bukan ramai-ramai menghukum.
Penutup
Kesalahan adalah bagian dari hidup manusia. Islam sudah lama mengakui itu. Tidak ada manusia yang lepas dari salah, kullu bani Adam khaththa’, kata Nabi ﷺ. Yang membedakan hanyalah bagaimana kita menyikapinya: apakah kita memperbaiki diri, atau justru larut dalam arus yang memperbesar luka orang lain.
Di era kamera di mana-mana, kesalahan kecil bisa berubah menjadi poster besar. Sebuah momen yang dulu hanya jadi bisik-bisik warung, kini bisa menjelma menjadi tontonan nasional. Kita memang tidak bisa mengendalikan semua ponsel yang mengintai, semua CCTV yang menyala, atau semua timeline yang sedang lapar drama. Tapi kita bisa mengendalikan adab, baik saat bertindak, maupun saat berbicara. Ini sejalan dengan pesan Islam: “Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam.” (HR. Bukhari & Muslim).
Kalau hidup ini panggung, kamera adalah penontonnya. Dan netizen? Mereka adalah komentator yang memegang mikrofon masing-masing, terkadang terlalu lantang, terkadang tanpa pertimbangan, sering kali lupa bahwa setiap komentar dapat menjadi beban hisab.
Karena itu, nilai-nilai Islam datang sebagai kompas: Tabayyun sebelum bicara. Agar kita tidak ikut menambah fitnah. Adil meski tidak suka. Agar hati kita tidak dikendalikan kemarahan. Menjaga kehormatan sesama. Agar kita tidak menjadi bagian dari kerusakan hidup orang lain. Tawadhu’ untuk mengakui salah. Agar opini kita tidak menjadi berhala baru. Dengan adab-adab ini, kita belajar menjadi manusia digital yang tidak hanya cepat, tapi juga bijak; tidak hanya vokal, tapi juga berakhlak; tidak hanya hadir di ruang publik, tapi juga membawa rahmat.
Pada akhirnya, lebih baik kita cerdas sebelum bicara, cermat sebelum viral, dan tenang sebelum hanyut dalam arus. Karena dalam perspektif Islam, bukan sekadar reputasi yang kita jaga, tapi juga nilai diri, akhlak, dan amanah sebagai hamba yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kata, baik yang diucapkan di lidah maupun yang diketik oleh jempol.
Referensi :
Bindra, S., Sharma, D., Parameswar, N., Dhir, S., & Paul, J. (2022). Bandwagon effect revisited: A systematic review to develop future research agenda. Journal of Business Research, 143, 305–317. doi: 10.1016/j.jbusres.2022.01.085
Brady, W. J., Wills, J. A., Jost, J. T., Tucker, J. A., & Van Bavel, J. J. (2017). Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks. Proceedings of the National Academy of Sciences, 114(28), 7313–7318. doi: 10.1073/pnas.1618923114
Brandwatch. (2025). Consumer Trends in the Media and Entertainment Industry. Diambil dari Brandwatch.com website: https://www.brandwatch.com/reports/media-and-entertainment-trends/
Dahl, R. A. (1998). On democracy. Connecticut: Yale university press.
Jenkins, H. (2006). Convergence culture: Where old and new media collide. New York: New York University Press.
Maddox, A., Sinanan, J., Carter, M., Horst, H., Spencer, M., & Wiesenfeldt, G. (2019). Cultural cosmologies of the Internet: Situating digital networked technologies in diverse moral universes. AoIR Selected Papers of Internet Research.
Marwick, A., & Boyd, D. (2017, Januari 4). The Drama! Teen Conflict, Gossip, and Bullying in Networked Publics. Open Science Framework. doi: 10.31219/osf.io/aknux
McIntyre, L. (2018). Post-truth. Cambridge: MIt Press.
Nickerson, R. S. (1998). Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. Review of General Psychology, 2(2), 175–220. doi: 10.1037/1089-2680.2.2.175
Papacharissi, Z. (Ed.). (2010). Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. Dalam A Networked Self (0 ed., hlm. 47–66). Routledge. doi: 10.4324/9780203876527-8
Stevenson, A. (2010). Oxford dictionary of English. Oxford University Press.
Trottier, D. (2017). Digital Vigilantism as Weaponisation of Visibility. Philosophy & Technology, 30(1), 55–72. doi: 10.1007/s13347-016-0216-4
Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science, 359(6380), 1146–1151. doi: 10.1126/science.aap9559
Zuboff, S. (2019). Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action. New Labor Forum, 28(1), 10–29. doi: 10.1177/1095796018819461